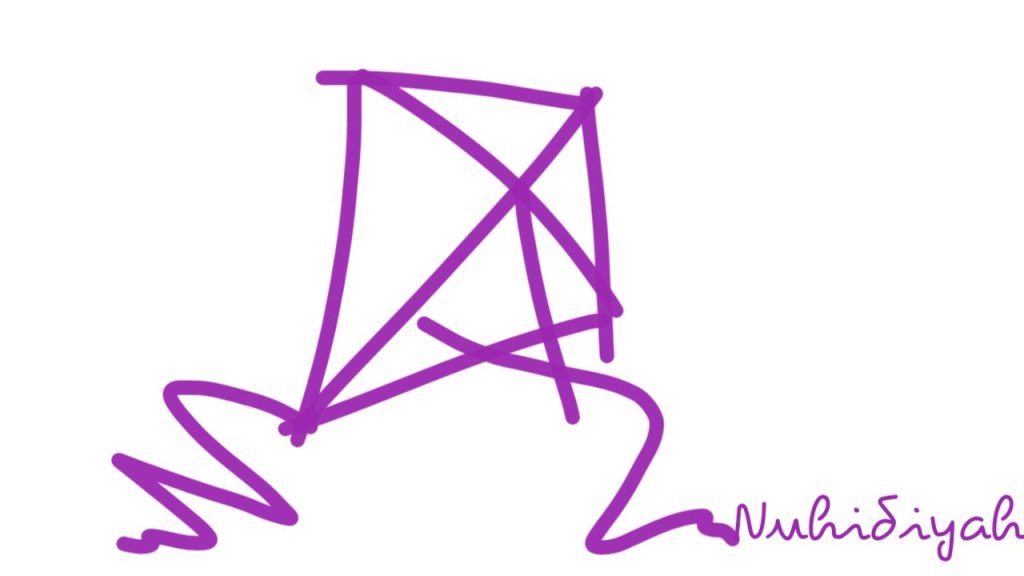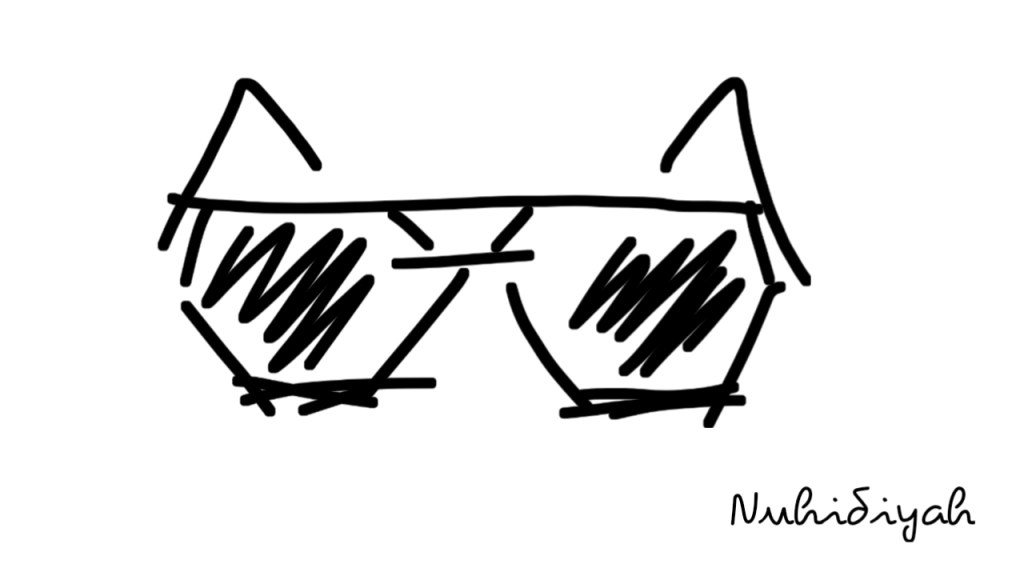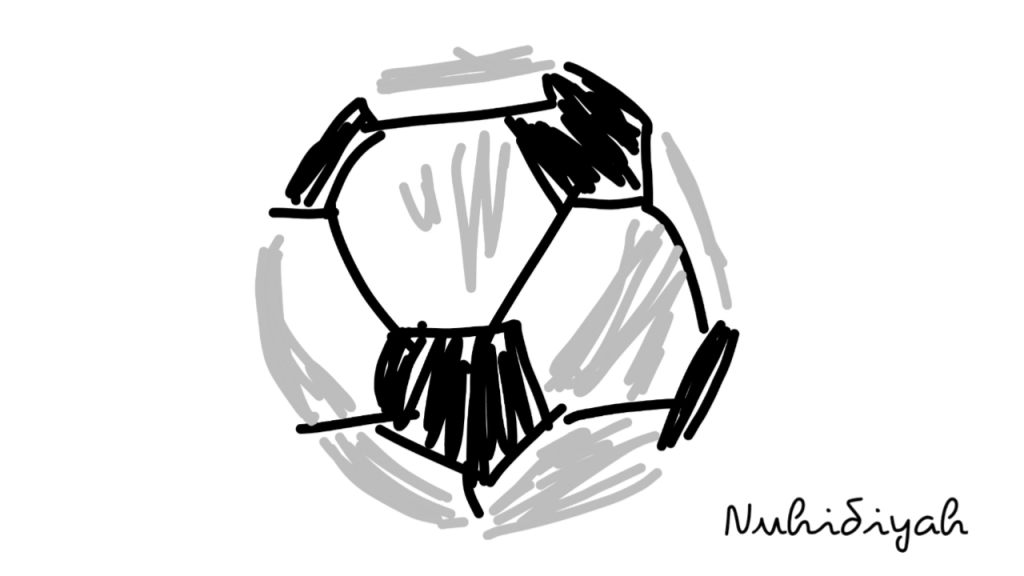Dari kecil, cita-cita saya memang menjadi kiai. Meskipun saat ditanya oleh para guru, saya menjawab “dokter” atau “tentara” karena nggak ada teman yang punya cita-cita seperti saya.
Mungkin karena bapak saya kiai. Saya mendengar, beberapa anak bercita-cita seperti profesi bapaknya. Ada yang cita-citanya jadi sopir, ada yang cita-citanya jadi petani. Saya langsung, “Ha?” Dan setelah tahu kejujuran atau kepolosan mereka itu, saya berpikir, kenapa saya harus malu bercita-cita menjadi kiai? Akhirnya dengan lantang saya revisi, “Saya tidak jadi bercita-cita menjadi dokter dan tentara. Saya pengen jadi kiai.”
Banyak guru yang mengaminkan. Dan alhamdulillah, doa-doa itu, kini terjawab.
Saya telah menjadi kiai. Tentu saja, dengan segala keterbatasan. Sungguh minder bila saya menyaksikan kiai-kiai yang telah matang. Tapi, bila saya tidak memasakkan diri mulai sekarang, kapan saya akan matang.
Dulunya, saya membayangkan, menjadi kiai itu bahagia. Tapi setelah saya rasakan, ternyata, lebih dari bahagia. Saya belum merasakan kebahagiaan seperti ini. Sebagaimana saya belum pernah merasakan perjuangan yang seberpetualang ini.
Menjadi kiai tidak bisa buat gaya-gayaan, berbeda dengan ustad selebritis atau mubalig keliling. Karena itu tidak jarang kita temui, kiai yang demikian ikhlas dalam berjuang. Saya awalnya tidak percaya adanya keikhlasan. Tapi dalam setiap ketidakpercayaan, kita akan selalu diantar pada satu titik yang memaksa kita untuk melepas percaya dan tidak percaya, menuju pada fakta. Seperti seorang lajang yang tidak percaya bahwa ada orang yang mencari uang dengan sulit, lalu uangnya tidak dinikmatinya sendiri. Sementara seorang suami dan ayah, tidak lagi butuh percaya. Seorang kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, hingga presiden, tidak butuh percaya, dan tidak butuh orang lain percaya. Orang lain, mungkin akan melempar tuduhan pada seseorang bahwa dia mengambil keuntungan dari takdirnya. Tapi yang dituduh, justru mendapat keuntungan tanpa mengambilnya. Keuntungan itu adalah kebahagiaan berjuang.
Yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapa pun adalah, belajar. Orang pandai, pintar, dan cerdas itu ada. Orang berilmu juga ada. Tapi tidak ada ilmu yang paripurna. Ilmu harus selalu dicari, sampai mati, bukan sampai jadi kiai.